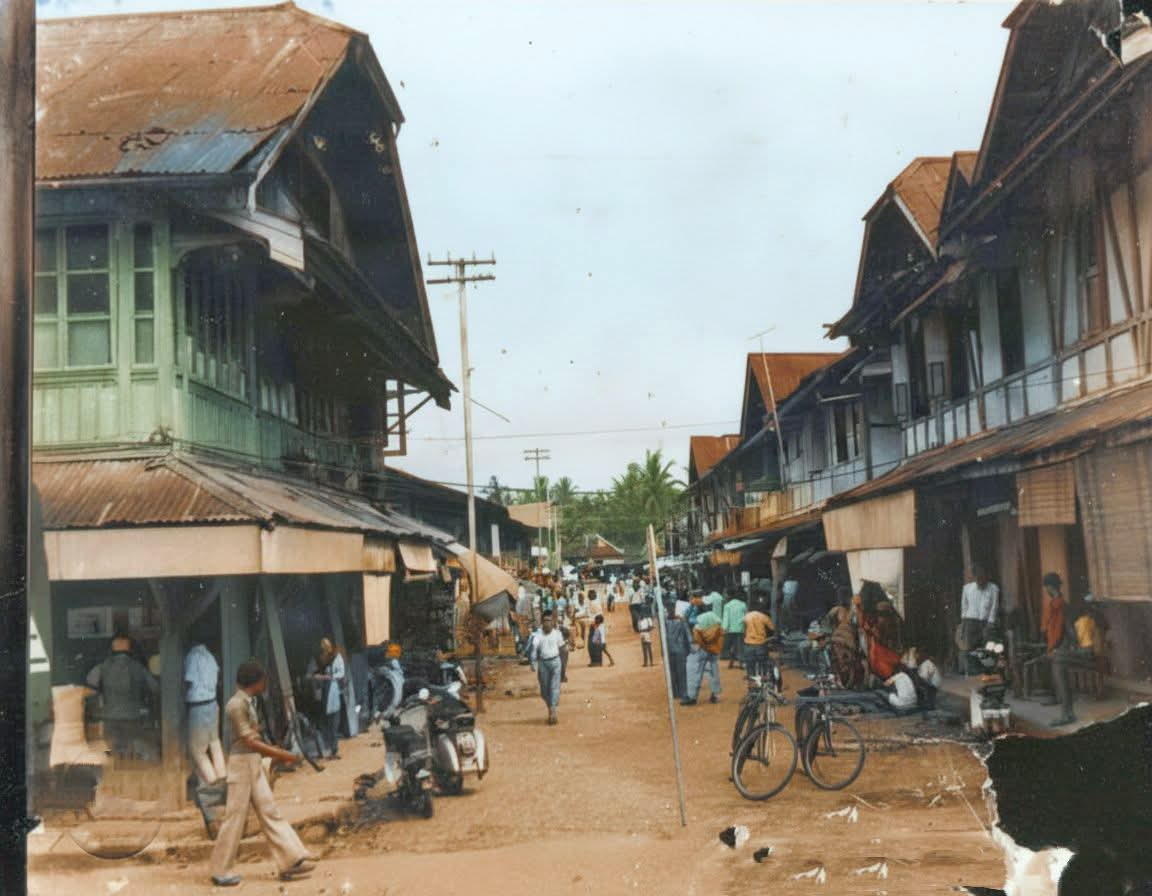Jeffrey Hadler, dalam karyanya Sengketa Tiada Putus: Matriarkat, Reformisme Islam, dan Kolonialisme di Minangkabau, menulis dengan gaya yang setajam risetnya. Buku yang awalnya merupakan disertasi di Cornell University itu, kemudian diterbitkan dengan judul asli Muslim and Matriarchs: Cultural Resilience in Indonesia through Jihad and Colonialism. Melalui karya ini, Hadler berusaha menyingkap bagaimana Minangkabau abad ke-19 membangun identitas sosialnya di antara tiga kekuatan besar: matriarkat, Islam reformis, dan kolonialisme Barat.
Dalam penggambaran Hadler, orang-orang kampung di Sumatra Barat kala itu hidup di bawah pergulatan nilai-nilai yang saling bertabrakan. Rumah dan keluarga menjadi ruang perdebatan tanpa akhir. “Keorangtuaan,” tulis Hadler, “diperdebatkan dan dinegosiasikan oleh ibu dan bibi, ayah dan paman.” Islam reformis dan negara kolonial sama-sama memihak patriarki, tetapi, kata Hadler, “mereka saling mencurigai satu sama lain.” Di tengah pertarungan itu, matriarkat Minangkabau mencari ruang bernapas di antara dua kekuatan ideologis yang sama-sama ingin mendominasi.
Reformisme dan kolonialisme menempatkan klaim kebenarannya pada otoritas universal pada “kebenaran-kebenaran absolut Quran dan Hadis dan pada gagasan-gagasan pasca-Pencerahan.” Namun, di sisi lain, matriarkat memandang diri sebagai sistem yang “bersifat lokal dan fluid,” terus menyesuaikan diri dengan ritme sosial dan spiritual masyarakatnya. Bagi Hadler, di sinilah ketegangan itu menjadi produktif: benturan ideologi justru melahirkan bentuk-bentuk baru pemahaman tentang keluarga, pendidikan, dan moralitas.
Dialektika tiga arah itu meluas jauh melampaui rumah gadang. Ia merembes ke surau-surau, sekolah-sekolah kolonial, dan ke dalam ruang batin anak-anak Minangkabau. “Anak-anak menghadiri sekolah yang hampir selalu menerapkan pedagogi-pedagogi yang bertentangan,” tulis Hadler. “Anak-anak perempuan dan laki-laki mendengar tentang matriarkat di rumah, belajar tentang Islam di surau, dan menerima pendidikan Eropa di sekolah-sekolah pribumi yang didirikan Belanda.”
Dalam suasana itulah, seorang bocah bernama Haji Agus Salim tumbuh di kampung Koto Gadang. Hadler menulis bahwa pada awal 1890-an, Salim telah menunjukkan kemampuan luar biasa dalam mengolah ketiga dunia pendidikan itu. Dalam satu kuliah yang dikutip Hadler, Salim mengenang masa kecilnya dengan renyah:
“Pendidikan agama saya sangatlah ketat. Di samping itu, di rumah ayahku saya juga mendapatkan ajaran agama tradisional sebagai anggota masyarakat Minangkabau… ketika pada umur 13 saya dilepas dari rumah untuk pergi ke sekolah menengah di Djakarta, saya telah menyelesaikan bagian pertama agama Minangkabau dan Muslim. Kemudian saya mulai persekolahan menurut aturan-aturan Barat… Saya pikir saya termasuk rombongan pertama kelinci-kelinci percobaan yang diuji dengan pendidikan barat…. Yah, saya pikir rombongan pertama ini cukup baik hasilnya.”
Kisah Salim hanyalah salah satu contoh dari apa yang disebut Hadler sebagai “transformasi pedagogis.” Bagi anak-anak Minangkabau, bersekolah bukan sekadar belajar membaca atau berhitung, tetapi perjumpaan dengan benturan ideologi antara Islam, adat, dan modernitas Barat.
Bahkan jauh sebelum kolonialisme menanamkan sistem pendidikannya, Minangkabau telah memiliki tradisi belajar yang mapan. “Bahkan di masa prakolonial,” tulis Hadler, “lembaga-lembaga keagamaan besar menarik murid-murid dari seluruh wilayah itu.” Namun ketika Belanda membangun jaringan sekolah pada akhir abad ke-19, terjadilah semacam “rantau pendidikan pra-dewasa.” Anak-anak muda mulai hidup di antara dua dunia: yang diwariskan adat dan yang dijanjikan modernitas.
“Adalah di sekolah-sekolah kampung Sumatra Barat,” tulis Hadler menegaskan, “bukan di akademi-akademi Belanda di Batavia dan Leiden atau universitas-universitas dan madrasah Kairo dan Mekah, intelektual-intelektual Indonesia pertama kali digodok.”
Narasi Hadler mengalir seperti laporan lapangan seorang penjelajah yang tak hanya mengamati, tapi juga menyelami denyut kebudayaan. Ia menulis sejarah Minangkabau bukan sebagai arsip mati, tapi juga berusaha melihatnya sebagai lanskap ideologis yang terus berdebat dengan dirinya sendiri antara rumah, surau, dan sekolah; antara ibu, paman, dan negara.